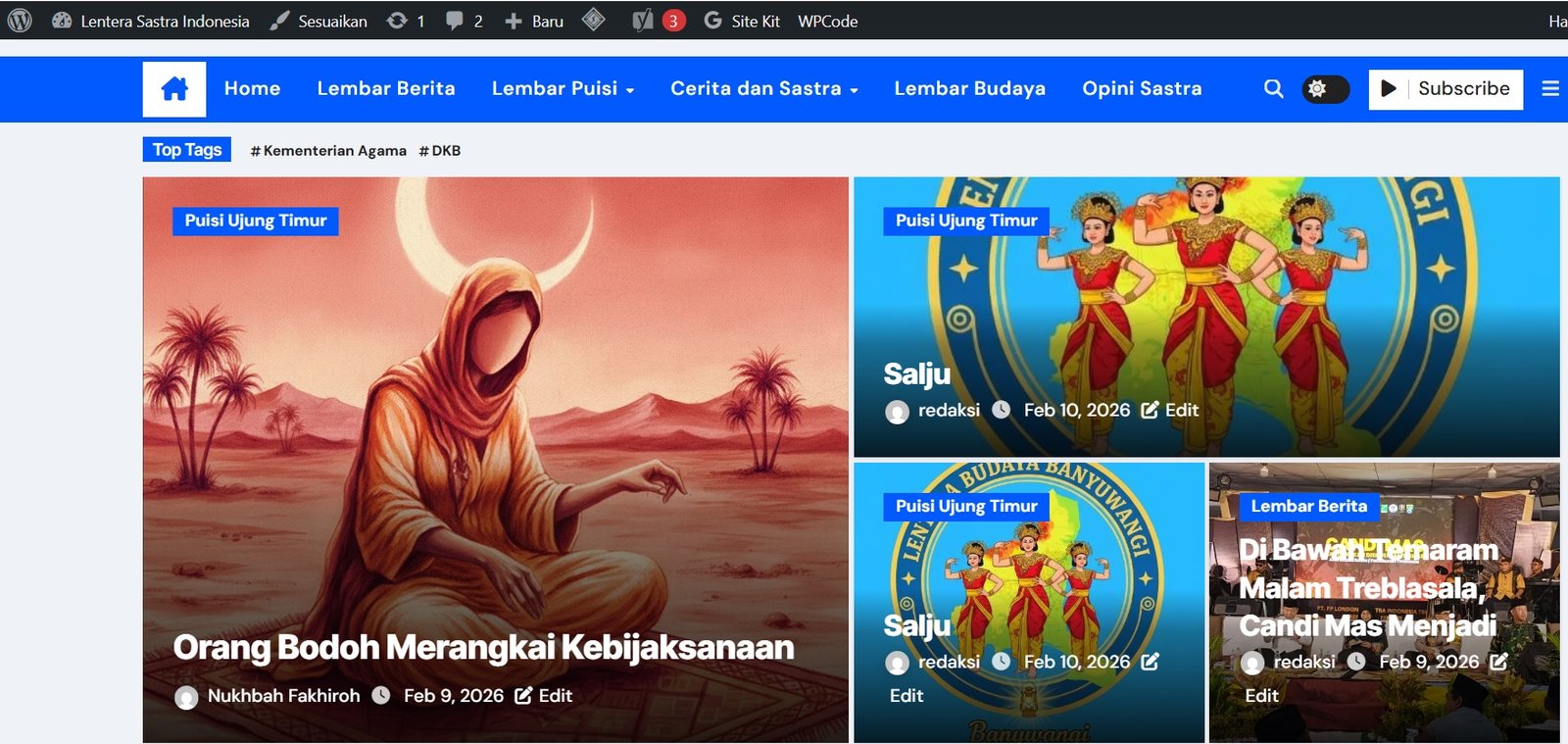Strategi Membranding Madrasah Melalui Media Digital
Oleh : Syafaat
Saya diminta mengisi kegiatan bertajuk Strategi Membranding Madrasah melalui Media Digital. Barangkali karena saya dianggap terlalu sering “hadir” di ruang-ruang digital, ruang yang kini lebih cepat dari gosip tentang seorang teman yang diam-diam selingkuh, dan lebih setia dari jam dinding di ruang tamu.
Hari ini, hampir tak ada manusia yang benar-benar asing dengan media digital. Ia telah menyusup ke lipatan hidup paling sederhana, menjadi perpanjangan tangan, bahkan perpanjangan napas. Telepon genggam yang tertinggal sering terasa seperti kehilangan separuh diri dan pikiran. Kita bisa lupa makan, lupa waktu, tetapi sulit lupa mengecek notifikasi. Ada anak yang lebih peduli pada layar daripada rasa lapar; ada orang dewasa yang lebih khusyuk menunduk pada ponsel daripada menengadah dalam doa.
Di titik inilah media digital kerap duduk di kursi terdakwa. Ia dituduh sebagai biang kerok turunnya prestasi, renggangnya relasi, hingga mengeringnya batin manusia modern. Tuduhan itu tidak sepenuhnya keliru. Namun juga tidak sepenuhnya adil. Sebab pada saat yang sama, media digital justru melahirkan anak-anak yang melesat prestasinya, membuka pintu ilmu yang dahulu terkunci rapat oleh jarak, biaya, dan keterbatasan ruang. Media digital, pada hakikatnya, hanyalah alat. Ia seperti pisau di dapur kehidupan: dapat menyiapkan hidangan yang menguatkan tubuh, dapat pula melukai tangan yang ceroboh. Yang menentukan bukanlah ketajaman bilahnya, melainkan arah tangan yang menggenggamnya. Alat selalu netral; manusialah yang memberi makna.
Agama mengajarkan kita tentang amanah. Segala sesuatu yang berada dalam genggaman manusia, harta, ilmu, waktu, bahkan teknologi, bukanlah milik mutlak, melainkan titipan. Media digital adalah amanah zaman. Ia datang membawa janji: akses informasi instan, jangkauan global, efisiensi yang mengubah cara manusia belajar, berdagang, dan berkomunikasi. Dalam satu sentuhan, ilmu berpindah benua. Dalam satu unggahan, pesan melampaui sekat geografis, agama juga mengingatkan tentang hisab. Tidak ada sesuatu yang dibiarkan berlalu tanpa pertanggungjawaban. Apa yang kita cari di media digital? Apa yang kita simpan, apa yang kita sebarkan? Apakah ia mendekatkan kita pada hikmah, atau justru memperpanjang kelalaian dengan bungkus hiburan dan ilusi pengetahuan?
Dalam dunia pendidikan, menjadikan media digital semestinya sebagai jembatan, bukan jurang. Ia dapat berfungsi sebagai dakwah sunyi: mengajarkan nilai tanpa teriak, membangun citra kebaikan tanpa merasa paling benar, memperluas pengaruh tanpa kehilangan adab. Lembaga pendidikan tidak cukup hanya saleh di dalam temboknya sendiri; ia harus cerdas membaca zaman agar nilai-nilainya sampai ke ruang-ruang baru yang kini dihuni generasi muda. Di sinilah kegelisahan itu lahir. Perubahan akan tetap terjadi, dengan atau tanpa persetujuan kita. Dunia tidak menunggu kesiapan siapa pun. Kita hanya diberi pilihan peran: menjadi penonton yang sibuk mengomentari, menjadi korban yang hanyut tanpa sadar, atau menjadi pelaku yang tahu arah dan tujuan. Agama tidak pernah mengajarkan ketakutan pada perubahan. Yang diajarkan adalah kebijaksanaan dalam menyikapinya. Media digital bukan musuh iman, melainkan ujian bagi kesadaran. Ia bisa menjadi ladang pahala, bisa pula menjadi sumber kelalaian, semuanya bergantung pada niat dan pengelolaan.
Karena itu, tugas kita, para pengelola lembaga pendidikan, para pendidik, sekaligus manusia yang memanggul iman, bukanlah menolak zaman dengan rasa curiga, melainkan menuntunnya dengan kesadaran. Zaman tidak pernah berhenti di gerbang masa lalu. Ia berjalan terus, kadang berlari, kadang tanpa menoleh ke belakang. Menolaknya hanya akan membuat kita tertinggal; membiarkannya tanpa arah akan membuat kita terseret.
Media digital, dalam konteks ini, tidak cukup dijadikan sekadar ruang eksistensi, tempat hadir agar terlihat, agar dianggap mengikuti arus. Ia mesti diubah menjadi ruang pengabdian: tempat nilai bekerja dengan sunyi, tempat akhlak menemukan bentuk barunya, tempat kebaikan disampaikan tanpa merasa paling benar. Bukan semata soal viral, tetapi soal makna. Bukan hanya soal ramai, tetapi soal arah. Sebab pada akhirnya, yang akan ditanya bukan seberapa canggih teknologi yang kita kuasai, melainkan untuk apa kecanggihan itu kita gunakan. Di hadapan Takdir, tak ada algoritma yang bisa menyamarkan niat, tak ada layar yang bisa menutupi tanggung jawab. Semua akan kembali pada pertanyaan paling mendasar: apakah teknologi itu mendekatkan kita pada hikmah, atau justru menjauhkan kita dari kesadaran?
Dalam upaya membranding madrasah melalui media digital, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence hadir bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kemungkinan. Ia adalah cabang ilmu yang berusaha meniru kemampuan kognitif manusia: belajar dari pengalaman, mengenali pola, memahami bahasa, dan membantu memecahkan masalah. Ia bekerja dengan mengolah data dalam jumlah besar, menemukan keteraturan di balik keruwetan, dan menawarkan efisiensi di tengah keterbatasan waktu manusia. Namun AI tetaplah mesin. Ia tidak memiliki nurani, tidak mengenal niat, tidak memahami makna di balik nilai. Karena itu, ia mesti ditempatkan sebagai asisten, bukan pengganti. Sebagai pembantu kerja, bukan penentu arah. AI dapat membantu menata kata, merapikan informasi, mempercepat proses; tetapi arah pendidikan, ruh madrasah, dan nilai keimanan tetap harus digenggam oleh manusia.
Madrasah yang bijak bukanlah madrasah yang menolak teknologi, tetapi madrasah yang menundukkan teknologi pada nilai. Menggunakan AI untuk memperluas jangkauan dakwah, memperkuat literasi, dan menyampaikan pesan kebaikan dengan bahasa zaman, tanpa kehilangan jiwa. Di sanalah teknologi menemukan maknanya, dan madrasah menemukan relevansinya. Karena sejatinya, teknologi hanyalah alat. Ia bisa menjadi cahaya atau bayang-bayang, tergantung siapa yang menyalakannya. Dan tugas kitalah memastikan bahwa cahaya itu tetap menerangi jalan, bukan membutakan arah.
Perubahan adalah takdir yang berjalan tanpa perlu meminta persetujuan. Sejak Heraclitus berbisik dari lorong filsafat Yunani bahwa tak ada yang abadi dalam perubahan selain perubahan itu sendiri, dunia seolah mengangguk setuju. Sungai tidak pernah sama meski kita menyebutnya dengan nama yang sama; airnya berganti, arusnya bergerak, dan kita yang menatapnya pun bukan lagi orang yang sama. Begitu pula kehidupan manusia. Musim berganti tanpa menunggu kesiapan petani. Waktu bergerak tanpa memedulikan nostalgia. Teknologi tumbuh lebih cepat daripada kemampuan kita untuk sepenuhnya memahaminya. Kita boleh menutup mata, tetapi perubahan tetap menemukan jalannya sendiri.
Karena itu, menolak perkembangan teknologi, bukanlah sikap bijak. Teknologi bukan sekadar alat; ia telah menjadi bahasa zaman. Anak-anak lahir di dalamnya, bernapas bersamanya, dan tumbuh dengan layar sebagai salah satu jendela pertama mereka mengenal dunia. Melarang secara total justru berisiko memutus mereka dari realitas yang sedang dan akan mereka hadapi, menerima bukan berarti membiarkan. Merangkul perubahan bukan berarti menyerah tanpa arah. Di sinilah kebijaksanaan diuji: bagaimana menempatkan teknologi sesuai usia, sesuai kebutuhan, dan sesuai kematangan jiwa anak. Kapan anak diberi kebebasan menjelajah dunia digital, dan kapan mereka perlu ditarik kembali ke dunia nyata, ke tanah, ke rumput, ke tawa yang tidak berfilter.
Ada masa ketika jari anak-anak seharusnya lebih akrab dengan mengmengan (permainan) daripada gawai, lebih mengenal layangan daripada layar, lebih sering menghitung langkah saat bermain petak umpet daripada menghitung likes. Permainan-permainan lama itu bukan sekadar nostalgia; ia adalah sekolah sunyi yang mengajarkan strategi, kesabaran, kerja sama, dan kekalahan yang diterima dengan lapang. Di sanalah otak diasah tanpa disadari, emosi dilatih tanpa dipaksa, dan sosialitas tumbuh tanpa algoritma. Anak-anak belajar membaca ekspresi, menunggu giliran, bernegosiasi, dan berdamai dengan perbedaan, pelajaran yang sulit diajarkan oleh layar datar.
Interaksi sosial sejati tidak lahir dari kolom komentar, tetapi dari tatap muka. Kepedulian terhadap lingkungan tidak tumbuh dari feed yang digulir tanpa henti, melainkan dari kaki yang menyentuh tanah, mata yang melihat langsung, dan tangan yang ikut merawat. Lingkungan bukan sekadar latar belakang foto, melainkan ruang hidup yang menuntut kehadiran. Media digital boleh menjadi pintu, tetapi ia bukan rumah. Ia dapat menjadi jembatan pengetahuan, tetapi bukan pengganti pengalaman. Anak-anak perlu diajari kapan harus masuk dan kapan harus keluar, kapan menggenggam dan kapan melepaskan.
Perubahan memang pasti terjadi. Tetapi arah perubahan tetap membutuhkan manusia yang sadar. Jika perubahan adalah arus, maka pendidikan, dan pengasuhan, adalah kemudi. Tanpa kemudi, kita hanya akan hanyut. Dengan kemudi, kita bisa sampai pada tujuan. Dan barangkali, di situlah tugas kita hari ini: bukan melawan perubahan, melainkan menuntunnya agar tetap manusiawi.
Penulis ASN Kementerian Agama / Ketua Lentera Sastra Banyuwangi